Mendesak pemerintah berpihak pada produsen kecil dan pangan lokal
oleh: Hartatik
Wonosobo – Agar pangan lokal seperti singkong diakui kalangan akademisi, menurut Prof Achmad Subagio dibutuhkan strategi khusus agar berkelanjutan di masyarakat. Terutama di kalangan milenials yang dengan mudah memperoleh makanan dari luar Indonesia.
Guru Besar Universitas Jember yang telah bergelut dengan singkong belasan tahun ini menyarankan, preferensi masyarakat tentang pangan harus diperbaiki. Untuk mendorong nilai, Prof Subagio merasa perlu lebih dikembangkan penyediaan pangan berbahan baku singkong melalui pemberdayaan UMKM pangan lokal. Khususnya, meningkatkan ketersediaan singkong dan olahannya sebagai substitusi pangan pokok.
“Kita perlu mereposisi pangan singkong menjadi pangan yang prestise. Tak hanya itu, rantai pasokan singkong juga diperbaiki, agar di hulu (petani) memiliki kepastian harga dan saluran distribusi dengan industri olahan. Langkah ini memerlukan kerja sama, komitmen stakeholder besar dan pemerintah pusat untuk sama-sama mewujudkannya,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini ada kesalahan dalam edukasi pangan terhadap masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat cenderung mengonsumsi nasi. Bukan hanya faktor harga, tadi telah ada kesan nasi lebih enak dan gaya hidup.
“Jadi ini persoalan persepsi. Kita perlu mengubah persepsi secara nasional terhadap pangan kita. Kalau tidak dilakukan sacara struktur dan sistematik, kita sulit. Ini yang melakukan harus pemerintah,” katanya.
Subagio yang dikenal sebagai profosser singkong ini juga melihat banyak kelebihan dari singkong. Karena gluten free, sehingga singkong baik untuk pangan masyarakat yang autis dan anti alergi. Singkong juga kaya serat yang baik untuk konsumsi masyarakat yang berpenyakit gula.
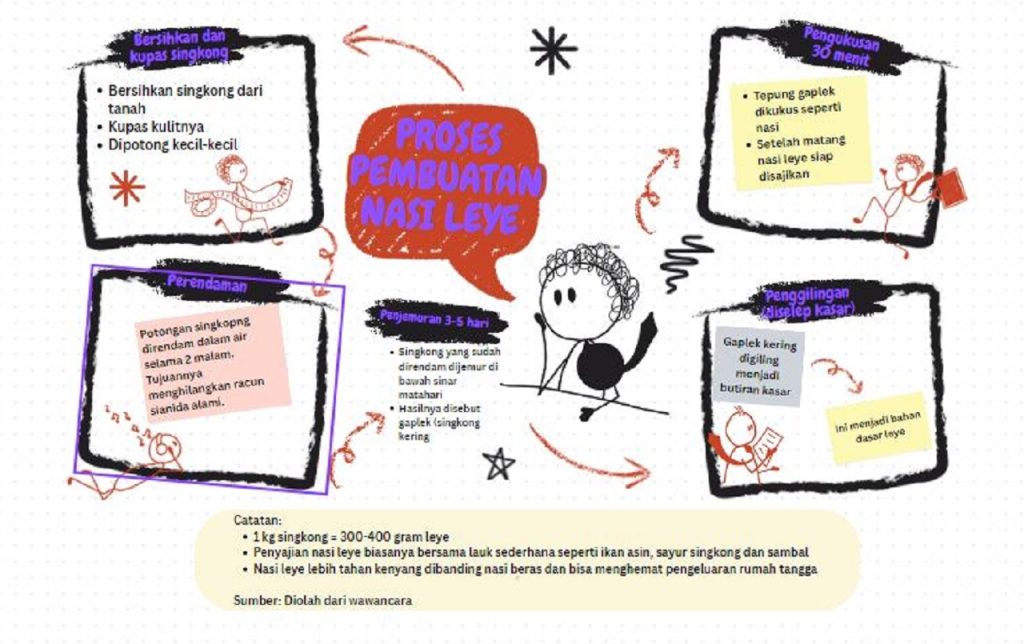
Hal senada diungkapkan Prof Fransiska Rungkat, Guru Besar Ilmu Pangan IPB University. Ia berpendapat bila nasi dapat digantikan dengan singkong 20 persen saja maka dapat turut menurunkan angka ketergantungan beras dan mengatasi ketahanan pangan. Terlebih singkong kaya akan vitamin dan mineral. Di dalamnya juga terdapat serat larut yang mengandung beta glucan dan memiliki aktivitas antikanker yang tinggi.
Jika melihat potensi singkong sebagai sumber karbohidrat substitusi nasi, peluangnya (sangat besar). Bahkan saat ini Indonesia merupakan negara penghasil singkong terbanyak keempat dunia.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional (NFA), Rinna Syawal mengungkapkan, pola konsumsi pangan penduduk pada 2023 untuk singkong masih rendah, yakni 9,7 kg/kap/tahun.
“Singkong sebagai salah satu komoditas umbi-umbian yang memiliki potensi untuk mendukung penganekaragaman pangan, terlebih masyarakat Indonesia di berbagai wilayah telah menjadikan singkong sebagai makanan pokoknya.”
Rinna pun menambahkan, NFA telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong potensi singkong dalam penganekaragaman konsumsi pangan lokal. Di antaranya implementasi Perpres 81 Tahun 2024 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, promosi konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman) dari pangan lokal, advokasi pemerintah daerah dalam pemanfaatan pangan lokal, bersinergi dengan asosiasi profesi serta pelaku usaha pangan lokal, dan pendampingan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pangan lokal.
“Mengonsumsi pangan lokal bukan hanya soal memenuhi gizi, tapi juga turut menggerakkan perekonomian, menjaga budaya, ramah terhadap lingkungan, dan yang tak kalah penting, mewujudkan kemandirian pangan bangsa.” tambahnya.
Regulasi ini semestinya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi penguatan pangan regional guna mendukung kedaulatan pangan nasional. Begitu pun sangat krusial bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengoptimalkan penggunaan pangan lokal yang sejalan dengan implementasi Perpres No 81/2024.
Namun sayangnya, implementasi regulasi itu tidak sepenuhnya berjalan optimal. Pasalnya, dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menggunakan bahan pangan lokal terfortifikasi sesuai karakter wilayahnya.
“Di kawasan pertanian seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, sumber karbohidrat utama berasal dari beras dan sayuran hijau, sedangkan di wilayah NTT dan Sulawesi, jagung, ubi, dan sagu menjadi bagian utama menu harian,” terang Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati.
Kebijakan ini tentunya semakin menggerus tradisi konsumsi nasi leye atau bahan pangan berbasis singkong di wilayah Jawa Tengah. Kondisi ini makin diperparah, di mana melalui proyek MBG, pemerintah tampak memposisikan pangan sebagai komoditas populis dan kendaraan politik.
Program yang seharusnya menjamin gizi rakyat justru dikelola secara sentralistik tanpa partisipasi publik yang bermakna, ditujukan kepada kelompok yang paling marjinal dan tanpa keberpihakan pada produsen pangan lokal.
“Kami mendesak agar pemerintah lebih berpihak pada produsen pangan kecil dan memperkuat sistem pangan lokal yang terbukti lebih berkelanjutan,” ungkap Koordinator Nasional FIAN Indonesia, Marthin Hadiwinata dalam forum memperingati Hari Pangan Sedunia 2025 sekaligus deklarasi pembentukan Koalisi Pangan Anti Cuan, Kamis (16/10).
Sementara itu, Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan, Irwan Fecho mengatakan, daerah memiliki sumber pangan lokal yang lahir dari interaksi panjang antara manusia dan alam, menjadi bagian dari kebudayaan yang diwariskan lintas generasi. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sendiri, mencatat Indonesia memiliki sekitar 945 jenis pangan lokal, di mana 77 jenis diantaranya merupakan sumber karbohidrat.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap daerah di Indonesia sesungguhnya memiliki “lumbung pangannya” sendiri,” katanya.
Meski begitu, keanekaragaman itu perlahan terpinggirkan. Pola konsumsi masyarakat makin seragam, dan memunculkan superioritas beras serta komoditas impor seperti gandum. Bapanas mencatat bahwa 97 persen penduduk Indonesia kini bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.
Ketergantungan seperti ini membuat sistem pangan rentan terhadap krisis iklim, gejolak global, hingga mengikis keanekaragaman pangan lokal yang menjadi identitas bangsa. Apalagi saat ini pemerintah tengah menggulirkan kebijakan MBG yang dipahami sebagian orang semata sebagai intervensi gizi untuk melawan stunting.
“Jika dicermati lebih jauh, MBG memiliki potensi besar sebagai titik ungkit strategis bagi transformasi sistem pangan kita.
Selain itu, jika dirancang berbasis potensi dan kearifan setempat, program MBG dapat menjalankan dua peran penting sekaligus. Pertama, menyediakan asupan gizi seimbang bagi anak-anak Indonesia. Kedua, menjadi penggerak ekosistem pangan lokal yang memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil di daerah.
Melalui pelibatan mereka sebagai pemasok utama, MBG dapat menciptakan pasar yang stabil, meningkatkan pendapatan keluarga tani, dan menghidupkan kembali diversifikasi pangan Nusantara. (Hartatik)
Baca bagian sebelumnya:
Bagian 2: https://tanahair.net/id/dari-desa-ke-media-sosial-cara-generasi-milenial-lestarikan-nasi-leye-2-3/
Bagian 3: https://tanahair.net/id/dari-desa-ke-media-sosial-cara-generasi-milenial-lestarikan-nasi-leye-3-3/
Foto banner: Siti Maryam menjemur tepung dari ubi kuning untuk diproduksi sebagai bahan tambahan tiwul instan di rumahnya, Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. (Hartatik)
“Liputan ini merupakan bagian dari Beasiswa “Journalist Fellowship and Mentorship Program for Sustainable Food System 2025″ yang didukung oleh Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bekerja sama dengan AJI Jakarta.”















