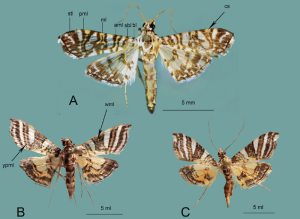Jakarta – Kelompok masyarakat sipil yang menilai kesepakatan dagang Indonesia–Amerika Serikat tidak hanya merugikan ekonomi nasional, tetapi juga melemahkan kedaulatan negara dan mendorong ketergantungan pada energi fosil. Organisasi advokasi Transisi Bersih menyebut skema perdagangan yang dirintis sejak era Donald Trump sebagai bentuk eksploitasi modern dalam balutan kesepakatan bilateral.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, Jumat, 25 Juli, menyatakan bahwa komitmen Indonesia untuk membeli gas senilai Rp244 triliun dari Amerika Serikat, sebagai imbal balik dari penurunan tarif impor menjadi 19 persen, tidak masuk akal dalam konteks geopolitik dan keberlanjutan ekonomi.
“Di satu sisi, Indonesia diminta membeli energi fosil dalam jumlah besar, sementara di sisi lain, AS justru membuka kran impor mineral kritis dari Indonesia tanpa hambatan tarif atau kuota. Ini adalah bentuk tekanan kebijakan atau state bullying, bukan kerja sama yang adil,” tegas Abdurrahman.
Ia menambahkan bahwa skema tersebut berpotensi menghambat program hilirisasi, yang selama ini menjadi tulang punggung strategi pembangunan industri nasional.
“Kita sedang membangun nilai tambah, tapi kesepakatan ini malah mengembalikan kita ke posisi sebagai pemasok bahan mentah. Ini jelas kontradiktif dengan cita-cita kedaulatan ekonomi,” lanjutnya.
Abdurrahman juga menyinggung UU No 3 Tahun 2020 tentang Minerba, khususnya pasal 170A yang mengatur bahwa ekspor mineral mentah hanya diperbolehkan hingga 2023. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya tidak dikompromikan dalam kesepakatan dagang yang memberi celah ekspor tanpa nilai tambah.
Senada dengan itu, Sartika Nur Shalati, analis kebijakan dari CERAH, menilai bahwa kesepakatan dengan AS justru menciptakan anomali regulasi, karena membuka ruang ekspor bijih mineral yang telah dilarang sejak 2020.
“Jika mineral kritis seperti nikel atau bauksit kembali diekspor dalam bentuk mentah, maka proyek hilirisasi akan terhambat, padahal itu adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja di sektor manufaktur dan teknologi kendaraan listrik,” kata Sartika.
Ia juga menilai bahwa langkah Indonesia membuka keran ekspor kepada AS justru berisiko menimbulkan tekanan dari negara lain, seperti Uni Eropa, yang sebelumnya memenangkan gugatan atas larangan ekspor bijih nikel di WTO.
“Bisa saja negara lain menuduh Indonesia memberikan perlakuan istimewa pada AS, dan menuntut hal serupa. Ujungnya, Indonesia harus membuka lagi ekspor bijih mentah ke negara lain. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Sartika menambahkan bahwa tata kelola lingkungan dalam industri mineral kritis saat ini masih lemah. Menurutnya, banyak perusahaan tambang belum memenuhi standar keberlanjutan, seperti transparansi emisi dan peta reklamasi. “Jika ekspor dibuka tanpa regulasi ketat, maka akan memperburuk krisis lingkungan yang sedang berlangsung,” tegasnya.
Sementara itu, Tata Mustasya, Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), mengingatkan bahwa kebijakan impor gas dari AS akan berseberangan dengan komitmen energi terbarukan dan swasembada energi yang digaungkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
“Impor gas dalam jumlah besar akan meningkatkan subsidi dan kompensasi listrik. Ini membuat fiskal kita makin terbebani dan memperlemah daya saing industri dalam negeri,” ujarnya.
Tata menekankan bahwa ketergantungan pada energi fosil dari AS akan membuat Indonesia kian terjebak dalam perangkap emisi.
“Uang negara seharusnya dipakai untuk mempercepat transisi energi, bukan memperkuat ketergantungan baru. Kalau ini diteruskan, maka mimpi Indonesia net zero emission tinggal slogan,” pungkasnya. (Hartatik)
Foto banner: Gambar dibuat oleh DALL-E OpenAI melalui ChatGPT (2024)