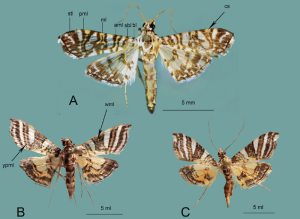Jakarta – Para pengamat energi terbarukan menyatakan bahwa target pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang masif perlu fondasi kebijakan dan pembiayaan yang kuat. Gagasan Presiden Prabowo Subianto membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebagai terobosan besar dalam agenda transisi energi dan pemerataan listrik dinilai masih terdapat berbagai ganjalan.
Ambisi yang mencapai total kapasitas hingga 80 gigawatt (GW) tersebut masih terganjal berbagai kendala mendasar mulai dari pembiayaan, kesiapan regulasi, hingga desain sistem kelistrikan nasional.
Lead Researcher SUSTAIN Indonesia, Adila Isfandiari, Senin, 15 Desember, menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki potensi sumber dana untuk mendorong realisasi target 100 GW energi surya, tetapi belum dikunci dalam kebijakan yang mengikat. Dikatakannya untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah perlu mengalokasian pembiayaan khusus untuk program ini di APBN.
Adila menjelaskan, salah satu opsi pembiayaan berasal dari peningkatan pungutan ekspor batu bara sekitar 5 persen mulai 2026, yang berpotensi menghasilkan penerimaan negara antara Rp 20 triliun hingga Rp 90 triliun per tahun dan dapat membiayai pembangunan PLTS di sekitar 18 ribu desa. Selain itu, pendanaan juga dapat dioptimalkan melalui kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) Cina, di mana alokasi sekitar Rp 14,4 triliun per tahun untuk energi terbarukan dinilai setara dengan pendanaan 32 proyek sekelas PLTS Terapung Cirata.
Climate Program Manager Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kiara Putri Mulia, mengingatkan bahwa ambisi besar tersebut tidak boleh dilepaskan dari kesiapan sistem kelistrikan nasional dalam menyerap energi surya. Ia menilai, tanpa reformasi struktural, penambahan kapasitas besar justru berpotensi menciptakan bottleneck baru.
“India dan Vietnam menunjukkan bahwa lonjakan kapasitas PLTS hanya mungkin terjadi jika kebijakan dan tata kelistrikan dibenahi secara menyeluruh,” kata Kiara.
Menurutnya, India berhasil karena memiliki kementerian khusus yang menangani energi baru dan terbarukan serta BUMN yang fokus mengimplementasikan target. Vietnam, di sisi lain, melakukan reformasi besar dengan membuka sistem kelistrikan melalui skema feed-in tariff yang menarik investor.
Pendanaan di tingkat desa
Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menilai rencana ini berpotensi terhambat karena kebutuhan investasi yang sangat besar. Jika dilengkapi dengan baterai penyimpanan, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai USD 250 miliar atau sekitar Rp 4.125 triliun.
Dwi menjelaskan bahwa biaya pembangunan PLTS 1 MW pada 2024 memang telah turun menjadi sekitar USD 900 ribu atau setara Rp 14,58 miliar, dibandingkan USD 1–1,5 juta pada tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih jauh melampaui kapasitas dana desa yang rata-rata hanya sekitar Rp 1 miliar per tahun, sementara kemampuan pembiayaan koperasi desa juga sangat terbatas.
“Artinya, walaupun dalam satu dekade terakhir harga panel surya global mengalami tren penurunan, namun tidak cukup untuk menutup kompleksitas risiko pembiayaan proyek desa,” jelas Dwi dalam diskusi bertajuk Menakar Kelayakan PLTS 100 GW, Analisis Teknis, Finansial dan Institusional.
Ia menambahkan, jika KDMP hanya memperoleh plafon pinjaman bank sekitar Rp 3 miliar dengan tenor enam tahun, jumlah tersebut tetap tidak mencukupi untuk menutup modal pembangunan satu unit PLTS 1 MW. Di sisi lain, perbankan nasional belum memiliki skema khusus untuk mengelola risiko proyek energi desa, sehingga proyek-proyek tersebut sulit dipandang sebagai aset yang bankable.
Untuk mengatasi persoalan ini, Dwi menilai pemerintah perlu merancang skema pembiayaan inovatif, salah satunya melalui penggabungan proyek atau project bundling agar lebih menarik bagi investor seperti green bond atau sukuk hijau dengan tenor 10 hingga 25 tahun. “Model bundling telah terbukti berhasil di Nigeria dalam mempercepat investasi energi terbarukan skala komunitas,” ujarnya.
Selain pendanaan, Dwi juga menyoroti peran KDMP yang perlu didefinisikan secara lebih realistis. Menurutnya, membebani koperasi desa sebagai pemilik sekaligus operator PLTS justru berisiko menciptakan masalah tata kelola, mengingat akan ada sekitar 80 ribu entitas berbeda yang membutuhkan audit, pemeliharaan, dan pengawasan.
Menurutnya, KDMP sebaiknya tidak dibebani tanggung jawab sebagai pemilik aset PLTS. Aset tetap dimiliki dan dioperasikan oleh pihak profesional seperti BUMN, IPP, atau perusahaan EPC berlisensi. Dalam skema tersebut, KDMP cukup berperan sebagai pembeli listrik atau off taker melalui tarif resmi seperti pelanggan PLN lainnya. Namun, menurut Dwi, hal itu kembali pada kesiapan kebijakan kelistrikan nasional.
Dengan besarnya tantangan investasi dan kompleksitas sistem, para pengamat menilai bahwa keberhasilan proyek PLTS desa bukan hanya ditentukan oleh besarnya target, tetapi oleh keberanian pemerintah membenahi regulasi, skema kelistrikan, dan arsitektur pembiayaan secara menyeluruh. (Hartatik)
Foto banner: Creativa Images/shutterstock.com