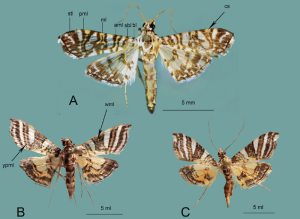Jakarta – Kubangan lumpur, desa yang hilang, dan jutaan warga yang kini mengungsi dari Aceh hingga Sumatra Utara menyisakan satu pertanyaan besar: apakah rangkaian banjir dan longsor itu benar-benar sekadar musibah alam? Para peneliti dan aktivis lingkungan menegaskan bahwa apa yang terjadi di Sumatra bukan takdir, melainkan konsekuensi dari krisis iklim yang diperburuk oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi masif di kawasan hutan strategis
Hingga 3 Desember 2025, tercatat 3,3 juta orang terdampak, 753 meninggal, 600 hilang, dan lebih dari 2 juta orang mengungsi, sementara kerugian material mencapai Rp 68,67 triliun menurut CELIOS. Berbagai jalur logistik terputus total, membuat bantuan sulit menjangkau wilayah terpencil.
Di saat yang sama, badai tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka—fenomena langka di garis khatulistiwa—menguat akibat suhu laut yang semakin hangat. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mencatat curah hujan ekstrem yang terjadi bersamaan dengan bencana ini merupakan anomali yang juga dialami Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Tekanan dari krisis iklim kian diperparah oleh deforestasi yang dipicu pembukaan hutan untuk tambang, sawit, dan hutan tanaman industri, membuat lanskap kehilangan daya serap air dan fungsi ekologisnya.
Kontras dengan beratnya situasi, Indonesia justru baru kembali dari Konferensi Iklim PBB di Belém membawa penghargaan “Fossil of the day”, dan delegasi dengan jumlah pelobi fosil terbesar dari seluruh negara peserta.
Di tengah kecaman publik, suara paling lantang datang dari kelompok masyarakat sipil. Sisilia Nurmala Dewi, Team Lead 350.org Indonesia, menyampaikan kritik keras kepada pemerintah yang dinilainya gagal melindungi rakyat dari bencana yang dapat dicegah.
“Banjir Sumatra bukan sekedar fenomena alam yang ditakdirkan Tuhan. Banjir ini adalah bencana buatan manusia yang didorong oleh pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Pemerintah Indonesia telah melukai rakyatnya dengan gagal melindungi hutan dan terus membiarkan penggunaan bahan bakar fosil, meski energi terbarukan telah tersedia dengan teknologi yang mumpuni dan harga yang semakin terjangkau,” ujarnya.
Sisilia mengatakan bahwa tindakan korektif harus dilakukan segera, mulai dari menghentikan izin industri ekstraktif hingga mengalihkan pendanaan negara dari fosil ke energi bersih. “Kami mendesak aksi nyata pemerintah menangani krisis iklim segera. Hentikan dan cabut izin sawit, tambang, dan hutan tanaman industri di kawasan hutan, gambut, ekosistem penting lainnya. Transisi energi sudah tidak boleh lagi sekedar omon-omon. Biayanya dalam bentuk bencana jauh lebih besar daripada pendapatan negara yang dihasilkan dari melanjutkan energi fosil,” katanya, dan menambahkan bahwa biaya pemulihan tidak boleh kembali dibebankan kepada masyarakat.
Nada serupa disampaikan Suriadi Darmoko, Field Organizer 350.org Indonesia yang juga penggugat dalam Gugatan Iklim Bali. Ia menyebut bencana di Sumatra sebagai bagian dari rangkaian cuaca ekstrem yang semakin sering dan mematikan.
“Kami berdiri bersama korban banjir Sumatra sebagai saksi bencana cuaca ekstrem makin sering dan intens. Dan kami menuntut pemerintah harus bergerak lebih cepat mengurangi—bahkan menihilkan—kerusakan dan kehilangan,” ucapnya.
Suriadi mengungkap bahwa masyarakat tidak diam menyaksikan kelalaian kebijakan negara. “Satu hal yang pasti, masyarakat tidak tinggal diam. Saya bersama Koalisi Pulihkan Bali mengajukan gugatan warga negara menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas banjir yang terjadi di Bali pada 10 September 2025 lalu dan memakan hingga 18 korban jiwa, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya,” katanya.
Dari Yogyakarta, suara pilu datang dari Arami Kasih, aktivis iklim dari Climate Rangers Jogja, yang keluarga dan kampung halamannya ikut terdampak. “Masalah tidak selesai saat banjir surut. Saya sendiri belum dengar kabar orang tua di lokasi terdampak. Akses terputus, listrik padam, jaringan hilang. Kampung lenyap, logistik menipis, air bersih langka,” tuturnya.
Arami menekankan bahwa krisis ini menunjukkan rapuhnya infrastruktur dan lambannya respon negara. “Sulitnya bantuan masuk ke wilayah dengan infrastruktur rusak dan tidak memadai menggarisbawahi kerentanan berlipat ganda yang dihadapi masyarakat di garis depan bencana ekologis ini,” ujarnya.
“Pemerintah harus tetapkan ini sebagai bencana nasional dan adili perusahaan penebang yang merusak serapan air di Kawasan Leuser—hutan lindung kita. Manusia, satwa, tumbuhan semua terdampak. Adili perusak ekosistem setegas-tegasnya!” katanya.
Arami menutup seruannya dengan peringatan keras bahwa cuaca ekstrem yang semakin intens tidak akan berhenti tanpa pertanggungjawaban global. “Curah hujan ekstrem juga faktor penyebab. Maka, negara kaya dan perusahaan pencemar harus bertanggung jawab,” tegasnya. (Hartatik)
Foto banner: Jalan tertimbun longsoran di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. 10 Desember 2025. Sumber: BNPB