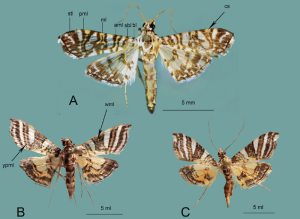Jakarta – Sebanyak 22 delegasi masyarakat adat Indonesia ambil bagian dalam Kongres Global Pertama Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal dari Tiga Cekungan Hutan Tropis Dunia (Three Basins Summit), yang digelar pada 26–30 Mei 2025 di Brazzaville, Republik Kongo. Dalam forum internasional ini, para penjaga hutan dari Amazon, Kongo, dan Asia Tenggara bersatu untuk menyuarakan peran penting masyarakat adat dalam penyelamatan iklim global.
Kehadiran delegasi Indonesia—yang merupakan bagian dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)—menjadi penegas posisi Indonesia sebagai salah satu wilayah dengan hutan tropis terluas dan komunitas adat yang aktif menjaga wilayahnya dari kerusakan.
“Kami datang membawa suara dari akar rumput. Krisis iklim tidak akan bisa diselesaikan tanpa melibatkan dan mengakui hak-hak masyarakat adat,” ujar Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN, yang turut hadir di kongres tersebut, dalam pernyataan tertulis, Jumat, 30 Mei.
Momentum sejarah untuk koalisi penjaga hutan dunia
Kongres ini digagas oleh Global Alliance of Territorial Communities (GATC) bekerja sama dengan Rights and Resources Initiative (RRI). Untuk pertama kalinya, masyarakat adat dari tiga cekungan hutan tropis—Amazon, Kongo, dan Borneo-Mekong-Asia Tenggara—berkumpul dalam satu forum global.
Sekretaris Eksekutif GATC, Juan Carlos Jintiach, menyebut forum ini sebagai tonggak sejarah. “Kami adalah koalisi hidup. Kami datang membawa pengetahuan leluhur dan pengalaman lapangan, yang selama ini menjaga bumi tetap bernapas,” ungkap Juan Carlos. “COP30 di Brasil nanti hanyalah satu titik dalam perjuangan panjang ini.”
Desakan atas pembiayaan langsung
Para peserta kongres menyoroti pentingnya pengakuan hukum atas wilayah adat, serta pembiayaan iklim yang langsung menjangkau komunitas di lapangan—bukan melalui mekanisme birokratis yang rumit. “Jangan bebankan masyarakat adat dengan administrasi berlapis. Itu akan melemahkan para penjaga bumi,” tegas Rukka, menyindir mekanisme iklim global yang kerap meminggirkan akar rumput.
Koordinator REPALEAC (jaringan komunitas adat di Afrika Tengah), Joseph Itongwa, menambahkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar pelengkap, melainkan pemimpin dalam pengelolaan krisis iklim. “Kami telah memperingatkan dunia sejak lama. Sekarang waktunya kami memimpin dengan pengetahuan dan pengalaman kami,” ujarnya.
Kongres dibuka dengan sesi khusus tentang kepemimpinan perempuan adat, yang dihadiri langsung oleh Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo. Ia menekankan pentingnya sinergi antara keberlanjutan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan keadilan sosial.
“Saya sangat menghargai perempuan adat yang tidak hanya menjaga hutan, tapi juga komunitas dan masa depan generasi,” ujar Matondo dalam pidatonya, 27 Mei.
Sebagai bagian dari agenda pra-Kongres, mekanisme pendanaan CLARIFI (di bawah RRI) mengumumkan alokasi USD 270.000 untuk mendukung inisiatif perempuan adat di delapan negara Afrika.
“Dana ini akan digunakan untuk regenerasi tanah, ekonomi lokal, dan restorasi keanekaragaman hayati,” jelas Deborah Sanchez, perempuan Moskitia asal Honduras sekaligus Direktur CLARIFI.
Kongres lima hari ini menjadi ruang strategis untuk mengukuhkan koalisi global masyarakat adat, menyusun Deklarasi Kongres, dan merumuskan Rencana Aksi Bersama untuk mendorong keadilan iklim berbasis wilayah adat.
Sara Omi Casama, pengacara Emberá dari Panama dan pemimpin gerakan perempuan GATC, menyebut kongres ini sebagai bentuk perlawanan berbasis harapan.
“Kami membela bumi dengan pengetahuan kami. Kongres ini memperkuat peran perempuan adat dalam tata kelola wilayah yang adil,” tegas Sara.
Senada, Levi Sucre Romero, warga masyarakat Bribri dari Kosta Rika, menambahkan: “Pengetahuan kami punya dasar ilmiah. Dunia harus berhenti menyederhanakan krisis iklim. Segalanya saling terkait, dan masyarakat adat berada di garis depan,” kata Levi, yang juga Direktur Aliansi Masyarakat Hutan Mesoamerika (AMPB).
Seruan dari Indonesia: Akar rumput bukan objek, tapi pemimpin perubahan
Di tengah ketimpangan pendanaan dan minimnya perlindungan hukum, delegasi Indonesia menyerukan pentingnya penempatan masyarakat adat sebagai subjek utama perubahan iklim. Mereka menuntut agar pengakuan wilayah adat dipercepat dan pendanaan iklim diarahkan langsung ke komunitas.
“Kami bukan objek bantuan. Kami pemimpin yang sudah terbukti menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Yang kami butuhkan adalah kepercayaan dan pengakuan,” ujar salah satu delegasi muda dari Kalimantan, Agus Wirayuda.
KTT ini akan ditutup dengan seremoni khusus yang menghadirkan kepala negara, donor global, dan mitra pembangunan, untuk menyaksikan komitmen bersama dalam Deklarasi Kongres Tiga Cekungan.
Dengan semakin dekatnya COP30 di Brasil, suara kolektif masyarakat adat dari tiga cekungan tropis terbesar di dunia ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam arsitektur keadilan iklim global. (Hartatik)
Foto banner: Pexels.com/AMAN