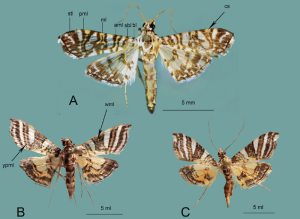Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa strategi yang diadopsi dalam Strategi Hidrogen Nasional (SHN) 2023 belum cukup fokus pada percepatan produksi hidrogen hijau sebagai bagian dari transisi energi berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 3.687 gigawatt (GW), yang dapat menjadi modal utama dalam pengembangan hidrogen hijau, hidrogen yang dihasilkan melalui elektrolisis air menggunakan energi terbarukan
IESR menilai bahwa hidrogen hijau memegang peranan penting dalam dekarbonisasi sektor industri dan transportasi, namun hingga saat ini, pengembangan hidrogen di Indonesia masih didominasi oleh hidrogen abu-abu, yang berasal dari gas alam dan memiliki jejak karbon tinggi.
“Indonesia sudah memiliki SHN, tetapi strategi yang dirancang masih lebih luas dan belum secara spesifik menargetkan percepatan pengembangan hidrogen hijau. Padahal, ini adalah kunci untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dalam diskusi “Mengidentifikasi Pasar Hidrogen Hijau di Indonesia”, Kamis, 30 Januari.
Fabby menjelaskan bahwa hidrogen hijau masih menghadapi tantangan biaya produksi yang tinggi dibandingkan hidrogen abu-abu. Untuk meningkatkan daya saing, ia menekankan pentingnya menekan biaya listrik dari energi terbarukan hingga di bawah USD 0,05/kWh, serta membangun infrastruktur hidrogen yang dekat dengan pusat konsumsi.
“Saat ini, harga gas bersubsidi untuk industri ditetapkan di angka USD 6 per MMBTU. Ini membuat hidrogen hijau kurang kompetitif dibandingkan hidrogen abu-abu yang diproduksi dengan harga lebih murah. Untuk itu, pengurangan subsidi gas dan penerapan harga karbon dapat menjadi strategi agar industri beralih ke hidrogen hijau,” ujar Fabby.
Pada tahun 2023, konsumsi hidrogen nasional diperkirakan mencapai 1,75 juta ton per tahun, di mana 88 persen digunakan untuk produksi urea, 4 persen untuk amonia, dan 2 persen untuk kilang minyak. Mayoritasnya masih menggunakan hidrogen abu-abu yang intensif karbon.
Fabby menambahkan bahwa langkah awal pengembangan hidrogen hijau bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan industri pupuk, semen, serta sektor yang sulit didekarbonisasi. “Kita harus mulai dari sektor yang sudah memiliki permintaan stabil agar produksi hidrogen hijau bisa bertumbuh dan mencapai skala ekonomi,” tegasnya.
Pembelajaran dari Inggris dan potensi Indonesia
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem hidrogen hijau, IESR bekerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam proyek Green Energy Transition Indonesia (GETI). Manajer GETI IESR, Erina Mursanti, menyoroti bagaimana Inggris telah sukses mendorong pasar hidrogen hijau melalui kebijakan seperti Low Carbon Hydrogen Standard dan Net Zero Hydrogen Fund (NZHF) senilai GBP 240 juta.
“Pemerintah Inggris menargetkan produksi 10 GW hidrogen rendah karbon pada 2030. Ini didukung oleh berbagai insentif, kerja sama dengan industri, serta riset dan pengembangan. Indonesia bisa mengadopsi strategi serupa untuk menarik investasi dan mempercepat transisi energi,” ungkap Erina.
Indonesia sendiri telah mengidentifikasi 17 lokasi potensial untuk produksi hidrogen hijau. Berdasarkan laporan Indonesia Energy Transition Outlook (IETO) 2025, biaya produksi hidrogen hijau di Indonesia diperkirakan berkisar antara USD 1,9 hingga 3,9 per kg pada tahun 2040. Angka ini lebih kompetitif dibandingkan rata-rata biaya global saat ini, yang berada di kisaran USD 2,7 hingga 12,8 per kg.
Namun, tanpa insentif yang tepat, hidrogen hijau tetap sulit bersaing dengan hidrogen fosil. “Diperlukan regulasi yang lebih jelas, dukungan kebijakan, serta target yang lebih ambisius untuk mempercepat transisi ke hidrogen hijau,” kata Erina.
IESR menekankan bahwa pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam mengembangkan hidrogen hijau melalui kebijakan yang jelas, insentif fiskal, serta penguatan iklim investasi.
“Ketergantungan pada bahan bakar fosil dalam produksi hidrogen akan meningkatkan emisi karbon dan berisiko menghambat transisi energi. Di sisi lain, ketergantungan pada gas alam juga mengancam ketahanan energi karena cadangan gas domestik yang semakin menipis,” pungkas Erina. (Hartatik)